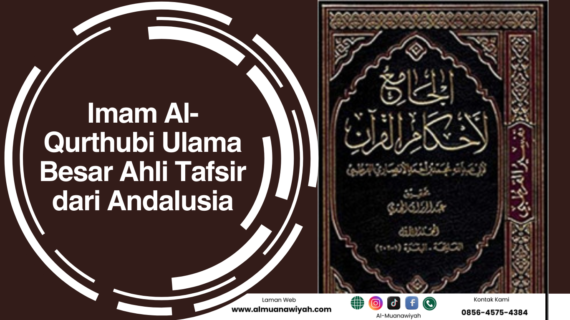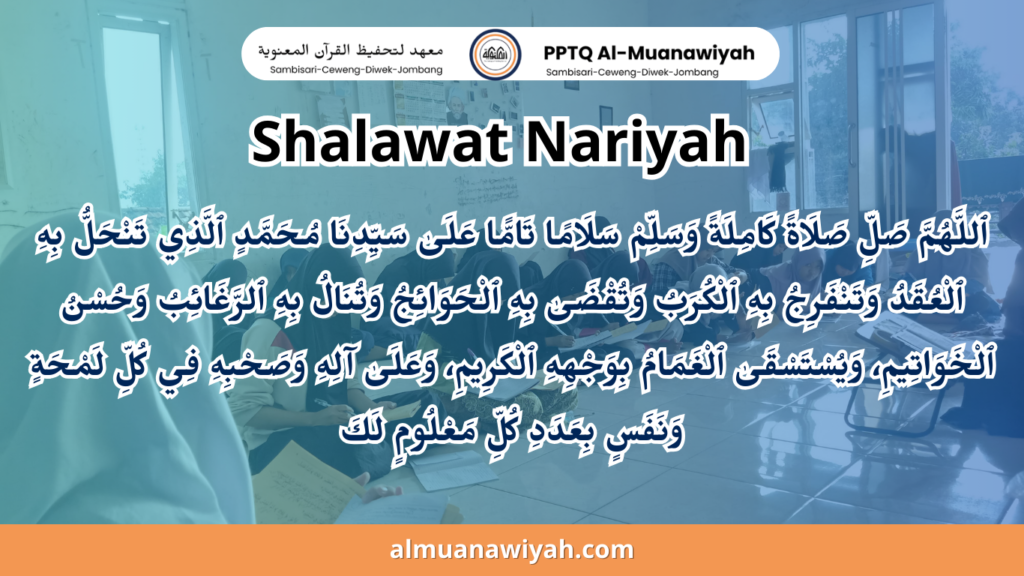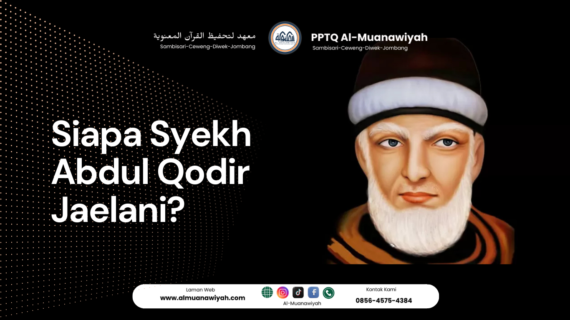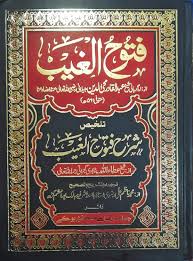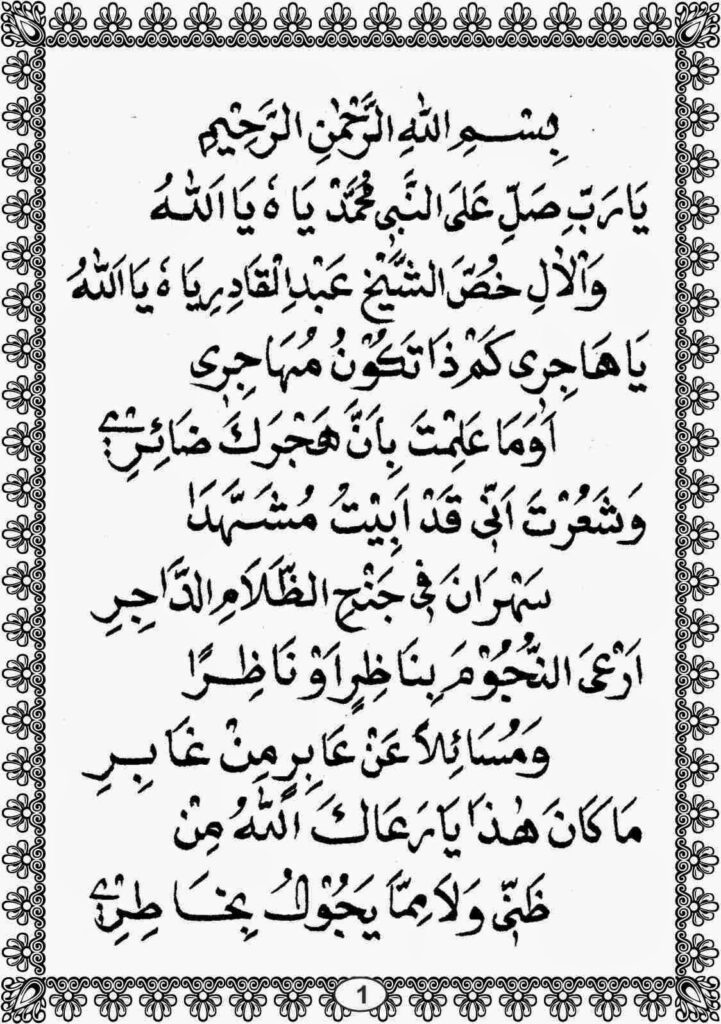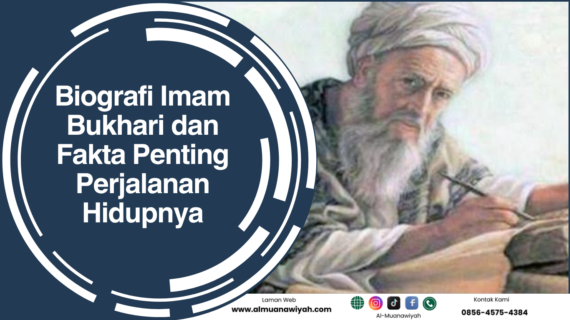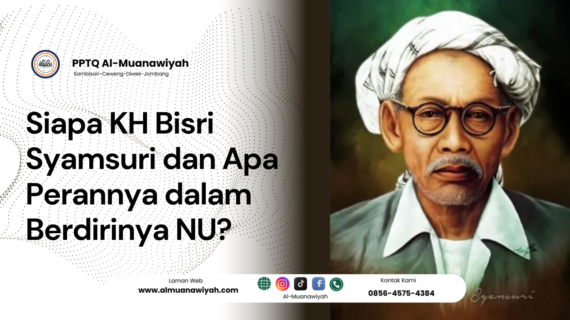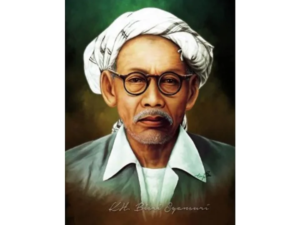Al Muanawiyah – Imam Al-Qurthubi adalah sosok ulama yang dikenal luas dalam dunia tafsir Al-Qur’an. Karya monumentalnya, Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, menjadi rujukan penting bagi para penuntut ilmu hingga hari ini. Artikel ini menyajikan biografi singkat, kontribusi ilmiah, serta pengaruh beliau dalam khazanah keilmuan Islam. Seluruh penjelasan difokuskan pada fakta sejarah yang telah dicatat oleh para sejarawan.
Biografi Singkat Imam Al-Qurthubi
Imam Al-Qurthubi memiliki nama lengkap Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Ansari Al-Qurthubi. Beliau lahir di Kordoba, Andalusia (Spanyol saat ini) pada awal abad ke-7 H. Kordoba pada masa itu merupakan pusat peradaban Islam Barat yang memiliki perpustakaan besar dan tradisi keilmuan yang kuat.
Beliau tumbuh di lingkungan masyarakat yang mencintai ilmu. Riwayat sejarah mencatat bahwa sejak usia muda, beliau sudah mempelajari hadits, fiqih Maliki, bahasa Arab, dan ilmu Al-Qur’an. Setelah kota Kordoba mengalami kekacauan politik, Al-Qurthubi berpindah ke Mesir. Di negeri inilah beliau mengajar, menulis, dan menghabiskan sisa hidupnya.
Imam Al-Qurthubi wafat di Minyat Bani Khashib, Mesir, pada tahun 671 H / 1273 M.
Baca juga: Biografi Imam Bukhari dan Fakta Penting Perjalanan Hidupnya
Karya-Karya Utama Imam Al-Qurthubi
Karya ilmiah beliau yang paling terkenal adalah:
-
Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an
– Tafsir fiqhiy yang menjelaskan ayat-ayat hukum secara rinci.
– Mencakup kajian tafsir, bahasa, qiroat, asbabun nuzul, dan pendapat para sahabat.
– Menjadi rujukan utama dalam studi fiqih lintas mazhab. -
At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah
– Membahas kematian, alam barzakh, hari kiamat, dan kehidupan akhirat.
– Banyak dikutip oleh ulama setelahnya seperti Ibnul Qayyim. -
Karya Hadits dan Ushuluddin
– Termasuk Al-Asma’ al-Husna dan penjelasan tentang tauhid.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya ahli tafsir, tetapi juga ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai bidang ilmu.

Metode Tafsir
Metode penafsiran beliau terkenal berimbang dan komprehensif. Ciri-cirinya antara lain:
-
Menyertakan dalil dari Al-Qur’an, hadits shahih, dan pendapat sahabat.
-
Menguraikan pendapat ulama mazhab, terutama Mazhab Maliki.
-
Memperhatikan aspek bahasa Arab, termasuk balaghah dan nahwu.
-
Memasukkan konteks sejarah dan asbabun nuzul.
-
Fokus pada hukum-hukum syariat yang terkait dengan ayat yang dibahas.
Pendekatan tersebut menjadikan karya tafsirnya diterima di berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia.
Pengaruh Imam Al-Qurthubi dalam Peradaban Islam
Pengaruh Al-Qurthubi terlihat dari penggunaan karya tafsirnya di:
-
Universitas Al-Azhar Mesir, sebagai rujukan studi tafsir.
-
Pesantren klasik dan modern di Nusantara.
-
Madrasah dan perguruan tinggi Timur Tengah.
-
Kajian kitab di masjid-masjid dan majelis ilmu.
Tafsir beliau juga menjadi salah satu rujukan resmi bagi para peneliti fiqih kontemporer ketika membahas ayat hukum.
Imam Al-Qurthubi hidup sederhana. Fakta sejarah mencatat bahwa beliau pernah mencari nafkah dengan menyalin kitab agar dapat membeli kebutuhan hidup dan buku. Semangat beliau dalam menuntut ilmu memberi inspirasi bagi generasi setelahnya untuk selalu disiplin dan tekun.
Beliau adalah ulama besar yang meninggalkan warisan ilmu sangat luas bagi umat Islam. Melalui karya tafsirnya yang mendalam, beliau membuka pemahaman tentang ayat-ayat hukum, nilai syariat, serta hikmah Al-Qur’an. Kontribusinya terus hidup dalam dunia pendidikan Islam hingga saat ini.