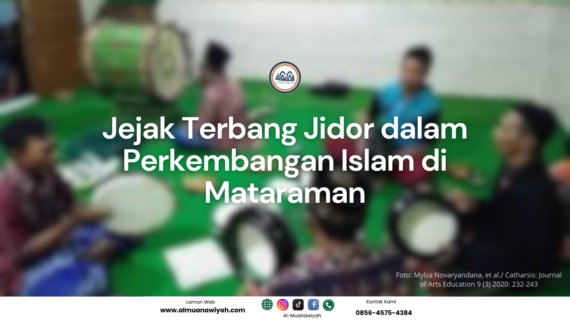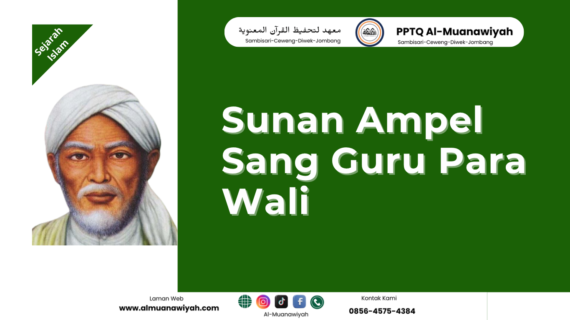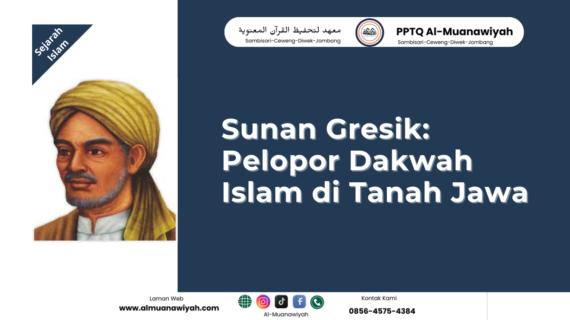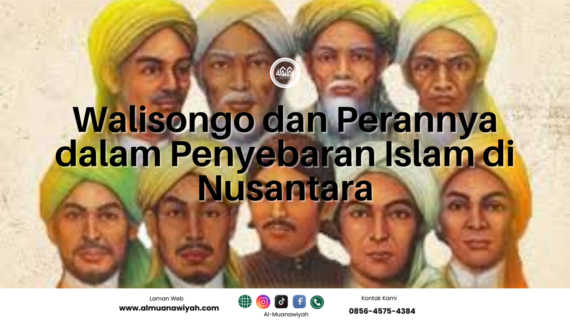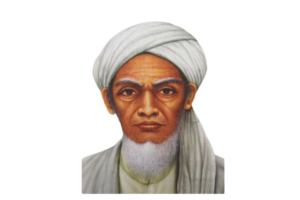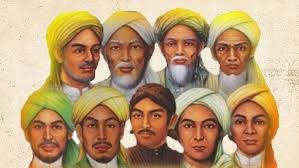Dalam deretan Walisongo, sosok Sunan Kudus memiliki keunikan tersendiri. Beliau bukan hanya dikenal sebagai pendakwah yang lembut dan toleran, tetapi juga sebagai seorang pemimpin militer yang tangguh. Kombinasi antara kedalaman ilmu agama dan keahlian strategi perang menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di tanah Jawa pada abad ke-16.
Siapakah sebenarnya Ja’far Shadiq dan bagaimana perjalanannya dari medan tempur menuju mimbar dakwah? Mari kita ulas lebih dalam.
Asal-Usul dan Silsilah Ja’far Shadiq
Sunan Kudus lahir dengan nama Ja’far Shadiq. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung (Panglima Perang Kesultanan Demak) dan Syarifah Ruhil. Dari garis keturunannya, beliau masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain.
Nama Ja’far Shadiq sendiri diyakini merujuk pada tokoh ulama besar di Madinah, yang menunjukkan bahwa sejak kecil beliau sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang alim.
Peran sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak
Sebelum menetap di Kudus, beliau menjabat sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Beliau mewarisi jabatan ayahnya setelah Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran melawan Majapahit.

Sebagai panglima, Sunan Kudus dikenal sebagai ahli strategi yang cerdik. Beliau memimpin pasukan Demak dalam berbagai ekspansi militer dan pertahanan wilayah. Keahlian inilah yang membuat beliau mendapatkan gelar Senopati Terung. Pengalaman di militer ini pula yang membentuk karakter beliau yang tegas namun tetap memiliki disiplin spiritual yang tinggi.
Baca juga: Jejak Terbang Jidor dalam Perkembangan Islam di Mataraman
Peran Sebagai Qadhi: Hakim Agung yang Adil di Kesultanan Demak
Selain memegang komando militer, sosok Sunan Kudus juga dipercaya menjabat sebagai Qadhi atau Hakim Agung di Kesultanan Demak. Jabatan ini membuktikan bahwa kapasitas intelektual beliau dalam bidang hukum Islam (Fiqh) diakui oleh para penguasa dan dewan Walisongo.
1. Penengah Konflik Keagamaan
Sebagai Qadhi, Sunan Kudus memiliki tanggung jawab besar dalam memutuskan perkara-perkara penting di kesultanan. Salah satu catatan sejarah yang paling masyhur adalah peran beliau dalam persidangan Syekh Siti Jenar. Beliau dikenal sebagai hakim yang sangat berpegang teguh pada syariat, namun tetap mempertimbangkan stabilitas sosial masyarakat Jawa yang baru saja mengenal Islam.
2. Ahli Fikih yang Moderat
Meskipun menjabat sebagai hakim agung dengan otoritas penuh, Sunan Kudus tidak bersikap kaku. Keahlian fikihnya justru beliau gunakan untuk mencari celah hukum yang memudahkan dakwah. Contohnya adalah ijtihad beliau dalam penggunaan arsitektur masjid dan tradisi kurban yang menyesuaikan kearifan lokal tanpa melanggar prinsip tauhid.
Transformasi Menjadi Ulama dan Strategi Dakwah
Setelah masa pengabdian militer yang panjang, beliau memutuskan untuk fokus pada dakwah. Beliau meninggalkan ibu kota Demak dan menetap di sebuah wilayah yang saat itu masih bernama Tajug. Kelak, wilayah ini diubah namanya menjadi Kudus, yang diambil dari nama Al-Quds (Yerusalem) di Palestina.
Baca juga: Sejarah Masjid Al Aqsa sebagai Kiblat Pertama Umat Islam
Strategi dakwah Sunan Kudus yang paling terkenal meliputi:
-
Pendekatan Kultural: Beliau tidak menentang tradisi lokal secara frontal.
-
Simbol Toleransi: Beliau melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai penghormatan kepada masyarakat Hindu yang mensucikan hewan tersebut.
-
Akulturasi Arsitektur: Membangun Menara Kudus dengan gaya candi agar masyarakat merasa akrab dengan bangunan Islam.
Ajaran dan Peninggalan
Selain Masjid Menara Kudus yang ikonik, sosok Sunan Kudus meninggalkan warisan pemikiran yang sangat berharga bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Beliau mengajarkan bahwa agama tidak seharusnya menghancurkan budaya lokal, melainkan mewarnainya dengan nilai-nilai tauhid.
Beliau juga dikenal sebagai pelopor teknik pertanian dan pertukangan di wilayah Kudus, yang membuat ekonomi masyarakat sekitar berkembang pesat.
Kesimpulan
Sosok Sunan Kudus adalah teladan sempurna tentang bagaimana kekuasaan dan kekuatan militer dapat bersanding harmonis dengan kelembutan dakwah. Beliau membuktikan bahwa menjadi seorang ulama tidak berarti meninggalkan realitas sosial dan politik, melainkan menggunakan pengaruh tersebut untuk menyebarkan kedamaian.